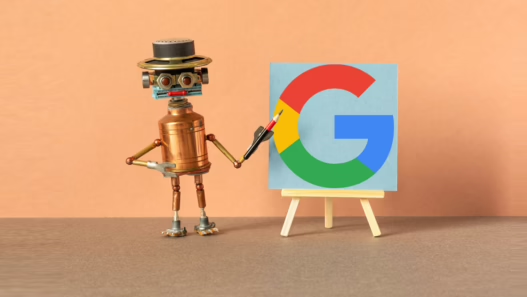Gaming di Era Dompet Menjerit: Kapan Harga Game Jadi Tidak Masuk Akal?
Kita semua pernah mendengar lelucon lawas tentang teknologi yang cyclical, alias berputar-putar. Kadang, dunia video game terasa seperti itu juga. Argumen dan kekhawatiran lama terus muncul, terutama soal… harga! Rasanya baru kemarin kita ribut soal harga game naik jadi Rp 1 juta. Wait, itu memang baru kemarin, kan?
Harga game selalu jadi perdebatan panas. Dulu, game NFL 2K5 bikin heboh karena dijual super murah sebagai respons terhadap perjanjian eksklusivitas. Sekarang, di era live-service dan free-to-play, harga tetap jadi isu sentral. Teknologi makin mahal, tarif bikin hidup susah, perusahaan terus PHK karyawan… tapi kita masih debat soal harga game baru. Ironisnya, backlog game di Steam kayaknya nggak akan habis-habis, jadi sebenarnya buru-buru beli game baru itu urgent atau impulsive?
Saya sendiri sudah sampai titik nggak mau bayar lebih mahal lagi untuk game baru. Kita sudah melewati batas, dan nggak ada jalan kembali. Gosip GTA 6 bakal jadi game pertama yang memecah bendungan kenaikan harga? Silakan saja. Saya nggak ikut-ikutan. Mendingan nabung buat liburan, siapa tahu ketemu easter egg tersembunyi di dunia nyata.
Game Baru Harga Selangit? Mending Skip Aja!
Hubris memang berbahaya. Beberapa perusahaan mungkin melihat peluang untuk menaikkan harga standar game triple-A karena ada konsol baru dan tarif impor yang naik. Microsoft sempat bikin heboh dengan pengumuman The Outer Worlds 2 bakal dijual Rp 1,2 juta! Untungnya, mereka buru-buru meralat dengan pesan tone-deaf di dunia game.
“Kami menerima sinyal SOS Anda tentang harga. Sebagai organisasi yang memastikan perusahaan tidak bertindak semena-mena, kami di Earth Directorate telah bekerja sama dengan [REDACTED] untuk merevisi harga The Outer Worlds 2.” Ew.
Saya nggak pernah suka seri ini, dan sekarang makin nggak suka. Lucunya, Microsoft dengan PD-nya berani mempertimbangkan langkah itu. Mungkin mereka lihat Nintendo berani pasang harga lebih tinggi untuk Mario Kart World di Nintendo Switch 2, tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Bundel Nintendo menawarkan nilai tambah, dan World adalah salah satu dari sedikit game eksklusif yang rilis bareng konsolnya.
Dan jangan lupa, The Outer Worlds juga bakal rilis di Xbox Game Pass. Tambah absurd, kan? Pertanyaannya sekarang: Apakah saya mau bayar mahal untuk game kalau hasilnya begini? Kalau ada game yang kualitasnya setara nasi goreng gerobak abang-abang yang bikin nagih, mungkin saya pertimbangkan lagi. Tapi kalau cuma sekelas makanan instan, mending saya masak sendiri.
Antara Gaming dan Krisis Separuh Baya
Bulan depan saya menginjak kepala empat. Cara saya menghabiskan uang dan waktu luang yang sangat langka jadi makin penting. Apakah saya mau menghabiskannya untuk video game yang makin mahal dan menyita waktu? Apakah saya mau menua di depan layar, atau menikmati senja dengan kopi dan buku?
Nilai sebuah game bagi konsumen, umumnya, dimulai dan berakhir saat mereka memainkannya pertama kali dan saat playthrough itu selesai. Memang ada pengecualian. Game yang bisa dimainkan selamanya. Game indie dengan pendekatan kreatif. Tapi sudah lama saya nggak merasa speechless gara-gara pengalaman triple-A yang tradisional.
Zaman sekarang, nyebut game itu AAA rasanya… ketinggalan zaman. Industri sudah berubah. Cara saya bermain sudah berubah. Yang lebih penting, fokus dan faktor yang membuat sebuah video game itu bergeser dengan cepat. Roblox adalah game terbesar di dunia, dan itu pada dasarnya adalah sweatshop video game.
Nostalgia vs. Realita: Dulu Game Lebih Greget?
Game free-to-play sudah jadi aturan, bukan pengecualian. Generasi gamer berikutnya – yang bahkan nggak menyebut diri mereka ‘gamer’, tapi penggemar pengalaman tertentu – nggak akan bermain game dengan cara yang sama. Mereka juga nggak akan bernostalgia dengan game dengan cara yang sama seperti generasi saya. Apakah kita sudah kehilangan esensi dari sebuah game?
Sepuluh tahun lagi, nostalgia mereka adalah untuk game seperti Cookie Run, Grow a Garden, dan Genshin Impact. Bukan untuk game full-priced yang besar dan mewah yang sudah berkuasa sejak saya remaja. Mungkin juga nostalgia untuk game yang nggak perlu bayar tapi bikin dompet jebol karena in-app purchases.
Ada sesuatu yang berubah di tengah jalan. Ancaman kenaikan harga terasa kurang seperti pemain mendapatkan nilai lebih, dan lebih seperti tantangan – seolah-olah publisher ingin melihat seberapa jauh mereka bisa melangkah. Ini bukan soal GTA 6 bukan selera saya, dan itulah kenapa saya menolak harga mahalnya. Sederhananya, saya nggak melihat proposisi nilainya. Pasar akan berbicara sendiri jika pemain setuju, tapi saya nggak akan ada di sana pada hari pertama.
Apa ini berarti saya selesai dengan gaming? Tentu saja tidak. Tapi saya butuh pengalaman yang lebih memuaskan dengan harga yang masuk akal. Rp 1,2 juta atau lebih untuk sebuah video game? No way. Saya bukan lagi anak umur 20 atau 30-an yang berusaha mengikuti media sosial dan teman-teman. Mending uangnya buat traktir keluarga, kan?
Harga Game Naik: Mending Jadi Kolektor, Bukan Day One Buyer
Intinya, harga video game memang naik, tapi nilai yang kita dapatkan belum tentu sebanding. Industri game terus berubah, dan mungkin sudah saatnya kita juga mengubah kebiasaan kita. Nggak perlu lagi jadi day one buyer. Mending jadi kolektor yang sabar menunggu diskon, atau gamer cerdas yang memanfaatkan subscription service kayak Xbox Game Pass. Kalau GTA 6 mau jual mahal, ya silakan. Saya mending main game di backlog atau cari game indie yang unik dan murah. See ya!