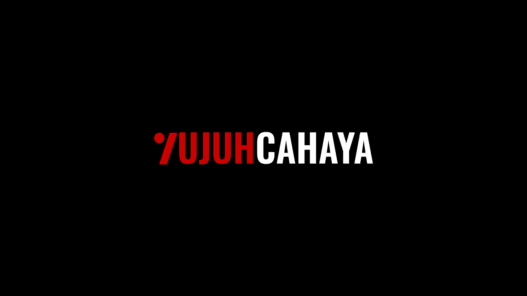Pertengkaran sengit mewarnai sidang di DPR pada 2 Juli 2025 lalu. Kali ini, bintangnya adalah adu argumen antara anggota DPR dari PDI-P, Mercy Chriesty Barends, dan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengenai komentar kontroversial sang menteri yang dianggap menampik adanya pemerkosaan massal dalam kerusuhan 1998. Bayangkan, baru ngopi pagi-pagi, eh sudah disuguhi drama sejarah.
Ketika Sejarah Jadi Arena Debat: Mengapa Ini Penting?
Mercy, yang juga merupakan anggota Komisi X DPR dan mantan investigator Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Tragedi 1998, menuding Fadli telah meremehkan pengalaman para korban dan kredibilitas investigasi yang sudah dilakukan. "Kalau kita bicara soal pemerkosaan massal 1998, itu menyakitkan. Saya adalah bagian dari tim yang mendokumentasikan kesaksian para korban," tegas Mercy dalam sidang tersebut.
Ia bahkan meminta sang menteri untuk mengunjungi Komnas Perempuan guna meninjau arsip laporan mereka, dan menuntut Fadli untuk meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap tidak menghormati para korban dan aktivis kemanusiaan. Ini bukan sekadar soal kata-kata, tapi tentang bagaimana kita menghargai memori kolektif bangsa.
Sebagai tanggapan, Fadli Zon mengklarifikasi bahwa komentarnya tidak bermaksud untuk menyangkal fakta sejarah, melainkan untuk mendorong narasi sejarah yang lebih "positif". Ia menekankan pentingnya menyoroti persatuan nasional daripada hanya berfokus pada peristiwa-peristiwa yang memecah belah. Intinya, positive vibes only, tapi apakah sejarah bisa di-filter seperti Instagram?
"Tujuan kita bukan melupakan sejarah, tetapi memastikan bahwa sejarah itu menjadi pelajaran yang konstruktif," ujar Fadli. "Saya tidak menyangkal apa yang terjadi. Saya sangat mengutuknya. Tetapi ketika kita menggunakan istilah seperti ‘pemerkosaan massal,’ kita harus mempertimbangkan implikasi hukum dan sejarahnya. Istilah itu menyiratkan tindakan yang sistematis dan terstruktur, seperti yang terjadi di Nanjing atau Bosnia," lanjutnya.
Fadli mengakui keberadaan korban dan mendukung dokumentasi serta pengakuan penderitaan mereka secara hukum. Namun, ia berpendapat bahwa penulisan sejarah harus menghindari narasi yang dapat membangkitkan kembali ketegangan etnis atau agama. Singkatnya, sejarah harus menjadi jembatan, bukan bom waktu.
Kontroversi ini tak berhenti di situ. Anggota Komisi X lainnya, sejarawan Bonnie Triyana, mengangkat kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan dalam proyek penulisan sejarah nasional. Ia menyoroti peran ganda Susanto Juhdi, yang menjabat sebagai editor teks sejarah saat ini dan juga editor "Kamus Sejarah" yang sempat menuai kontroversi.
Dualisme Peran Editor Sejarah: Aroma Konflik Kepentingan?
"Saya pikir itu adalah bagian dari masalah," kata Bonnie, mempertanyakan integritas proses editorial di bawah pengawasan Kementerian Kebudayaan. Bayangkan, tugas membuat sejarah, eh malah ada potensi bumbu-bumbu kepentingan pribadi.
Menanggapi hal ini, Fadli menjauhkan diri dari keputusan editorial langsung, mengatakan bahwa ia tidak campur tangan dalam konten atau pemilihan personel. "Silakan tanya para sejarawan sendiri apakah saya melakukan intervensi. Bahkan ketika menyangkut istilah seperti ‘Orde Lama’, saya bertanya apakah istilah semacam itu bahkan ada pada waktu itu," ujarnya. Agak defense mode, ya?
Ia kembali menegaskan bahwa tujuan dari narasi sejarah baru adalah untuk menyajikan pencapaian Indonesia, seperti Konferensi Asia-Afrika, sebagai bagian dari potret masa lalu bangsa yang lebih luas dan seimbang. Jadi, intinya, jangan cuma lihat sisi kelamnya, tapi juga sisi gemilangnya.
Menggali Lebih Dalam: Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Lantas, apa sebenarnya yang menjadi inti dari perdebatan ini? Apakah ini sekadar perbedaan pendapat tentang terminologi, atau ada isu yang lebih mendalam? Bisa jadi ini adalah perdebatan tentang bagaimana kita seharusnya menceritakan sejarah kita sendiri. Apakah kita harus fokus pada kesalahan masa lalu untuk memastikan hal itu tidak terulang kembali, atau haruskah kita menyoroti pencapaian kita untuk membangun rasa bangga nasional?
Perdebatan tentang pemerkosaan massal 1998 sangat sensitif karena menyangkut pengalaman traumatis para korban dan keluarga mereka. Menggunakan istilah yang tepat dan akurat sangat penting untuk menghormati penderitaan mereka dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa penggunaan istilah tertentu dapat mempolarisasi masyarakat dan menghambat upaya rekonsiliasi nasional.
Menulis Ulang Sejarah: Misi Mustahil atau Peluang Emas?
Proyek penulisan sejarah nasional selalu menjadi isu yang kontroversial. Siapa yang berhak menentukan narasi sejarah yang "benar"? Bagaimana kita memastikan bahwa semua perspektif diperhitungkan? Dan yang paling penting, bagaimana kita menghindari distorsi atau bias yang dapat merugikan kelompok tertentu?
Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama, tantangan ini menjadi semakin kompleks. Sejarah kita dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dan kontroversial, mulai dari penjajahan hingga konflik etnis dan agama. Menemukan cara untuk menceritakan kisah-kisah ini secara jujur, akurat, dan inklusif adalah tugas yang monumental.
Belajar dari Masa Lalu, Menuju Masa Depan yang Lebih Baik
Pada akhirnya, perdebatan antara Mercy Chriesty Barends dan Fadli Zon adalah pengingat bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang statis atau monolitik. Sejarah adalah narasi yang terus-menerus dinegosiasikan dan diinterpretasikan ulang. Penting bagi kita untuk terus belajar, berdiskusi, dan berdebat tentang masa lalu kita agar kita dapat membangun masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan sejarah di-edit sepihak, karena masa depan ada di tangan generasi yang melek sejarah.