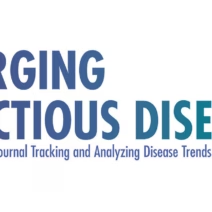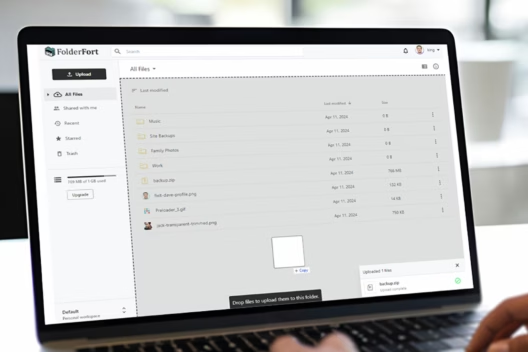Bayangkan begini: tiap pagi kita bangun, langsung otomatis nyalain “mesin kebebasan” pribadi, lalu terjebak macet sambil nyinyir ke pengendara lain. Ironis? Banget. Mobil, yang katanya simbol kemajuan, ternyata punya efek samping kayak cheat code yang bikin hidup makin susah.
Mobil: Antara Kebebasan dan Jebakan Batman
Dulu, punya mobil itu kayak punya infinity stones. Ke mana aja bisa, kapan aja bebas. Tapi sekarang? Lebih mirip langganan Netflix: tiap bulan nguras dompet buat sesuatu yang sebenernya bikin kita makin mager di rumah. Biaya perawatan, bensin, parkir, belum lagi risiko penyok karena tetangga yang parkirnya kayak main gacha. “Freedom” macam apa ini?
Industri mobil emang jago banget bikin kita kecanduan. Mereka jual mimpi tentang petualangan dan status sosial. Padahal, di balik kemudi, kita cuma jadi pion dalam permainan ekonomi, politik, dan budaya yang mereka atur. Kita pikir kita yang nyetir, padahal kita yang disetir.
Dan jangan salah, punya mobil itu bisa bikin miskin. Bukan cuma karena cicilan yang kayak setan nagihnya, tapi juga karena duitnya nggak bisa dipake buat investasi yang lebih penting. Kebayang nggak, uang muka mobil bisa buat beli tanah kavling atau modal usaha kecil-kecilan? Tapi ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur, mobil sudah jadi beban.
Fenomena “car poor” ini nyata banget. Banyak orang yang penghasilannya pas-pasan, tapi maksain punya mobil demi gengsi atau tuntutan kerja. Alhasil, tiap bulan hidupnya kayak main survival horror: mikirin gimana caranya bayar cicilan, bensin, dan tetek bengek lainnya. Padahal, kalo dipikir-pikir, naik angkot atau ojek online juga nggak kalah praktis, malah bisa sambil dengerin musik atau podcast.
Solusi Mobil Listrik dan Otonom: Sekadar Ganti Baju?
Katanya, mobil listrik dan otonom itu solusi masa depan. Nggak ada polusi, nggak perlu nyetir sendiri, tinggal duduk manis sambil main TikTok. Tapi, apa bener gitu? Apa cuma ganti bensin jadi listrik dan setir manual jadi autopilot udah bisa nyelesain semua masalah?
Henrietta Moore dan Arthur Kay, penulis buku “Roadkill: Unveiling the True Cost of Our Toxic Relationship with Cars,” punya pandangan yang lebih kritis. Mereka bilang, mobil listrik dan otonom itu nggak ngebongkar akar masalahnya, cuma ganti bungkusnya doang. Tetep aja, kita masih tergantung sama mobil, masih butuh infrastruktur jalan yang mahal, dan masih berpotensi jadi korban peretasan.
Bayangin aja, mobil otonom diretas, terus berubah jadi senjata pembunuh massal. Lebih serem dari boss battle di game RPG manapun, kan? Belum lagi masalah privasi. Data kita direkam, dianalisis, dan dijual ke pihak yang nggak bertanggung jawab. Kita jadi komoditas, dan mobil jadi mata-mata.
Terus, soal keamanan, mobil masih jadi momok. Menurut “Roadkill,” mobil udah ngebunuh 60-80 juta orang sejak ditemukan. Lebih banyak dari korban Perang Dunia I dan II digabung. Dan tiap tahun, jutaan orang luka-luka karena kecelakaan mobil. Data dari National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) tahun 2019 aja nyebutin ada 36.500 orang tewas dan 3.1 juta orang luka-luka.
Dampak Ekonomi dan Lingkungan: Lebih dari Sekadar Isi Dompet
Nggak cuma nyawa, mobil juga ngerusak ekonomi dan lingkungan. NHTSA ngitung, total kerugian sosial akibat kecelakaan mobil di tahun 2019 mencapai $1.37 triliun. Itu empat kali lipat dari dampak ekonomi langsungnya. Dan 75% dari kerugian itu adalah “kehilangan kualitas hidup.” Artinya, duit nggak bisa ngobatin trauma dan kesedihan.
“Road Kill” juga nyebutin dampak lingkungan dari mobil. Polusi udara, ekstraksi sumber daya alam (minyak, baja, lithium, cobalt), dan perubahan iklim bikin kesehatan semua orang makin parah. Mobil emang kontributor CO2 terbesar. Dan buat bikin satu mobil aja, butuh 0.9 ton baja.
Ekstraksi bahan buat mobil listrik juga nggak kalah ngeri. Lithium dan cobalt ditambang di negara-negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Prosesnya nyebabin polusi air tanah dan kerusakan lahan. Ironisnya, kita pengen nyelametin lingkungan, tapi malah ngerusak tempat lain.
“U-Turn”: Saatnya Putar Balik?
Terus, gimana dong? Apa kita harus balik lagi ke zaman kuda dan pedati? Nggak juga. Tapi, kita perlu “U-turn,” kata Moore dan Kay. Kita harus ngubah cara pandang kita tentang mobil dan mobilitas. Kita harus bikin kota yang lebih manusiawi, yang ngutamain pejalan kaki, sepeda, dan transportasi umum.
Konsep “15-minute city” bisa jadi solusi. Di kota kayak gini, semua kebutuhan kita – kerja, belanja, sekolah, taman, kesehatan – bisa dijangkau dalam 15 menit dengan jalan kaki, sepeda, atau transportasi umum. Lingkungan jadi lebih sehat, sosial, dan manusiawi.
Tapi, buat ngewujudin itu, kita butuh investasi publik yang besar di transportasi alternatif. Duit pajak yang biasanya buat bikin jalan tol dan jembatan layang, dialihin buat bikin jalur sepeda, trotoar yang nyaman, dan transportasi umum yang terjangkau. Emang nggak gampang, ngelawan “car-industrial complex” itu kayak ngelawan final boss yang curang banget. Tapi, ada jalan kok. Kita bisa bikin masyarakat yang lebih sehat, adil, dan sejahtera.
Dame Henrietta L. Moore, seorang pemikir global tentang kemakmuran, dan Arthur Kay, seorang pengusaha dan desainer kota, adalah dua orang yang ngajak kita buat mikir ulang tentang hubungan kita sama mobil. Mereka ngasih kita peta jalan buat perubahan, dari kota yang ramah mobil jadi kota yang ramah manusia.
Jadi, kapan kita mau “U-turn”?