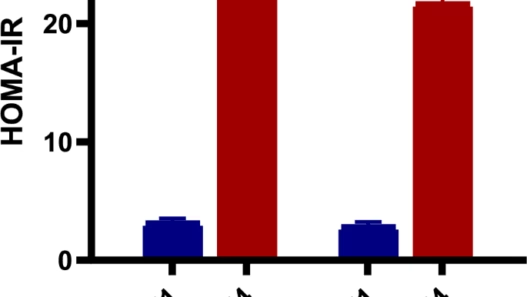Bayangkan saja, hidup ini seperti lagi maraton sprint menuju deadline yang padat, lalu tiba-tiba di tengah jalan, sponsor utama cabut semua logistik dan minumannya. Nah, kejadian serupa, tapi jauh lebih dramatis, baru saja menimpa ribuan orang di Afrika Selatan. Di Johannesburg, kabar beredar secepat kilat: klinik-klinik nirlaba penyedia layanan HIV gratis bakal tutup dalam 24 jam, gara-gara ‘ketok palu’ dari Presiden Donald Trump yang mengumumkan pemotongan bantuan asing Amerika Serikat. Ini bukan sekadar plot twist ala sinetron, tapi realitas pahit yang membuat banyak nyawa terancam dalam apa yang bisa kita sebut sebagai ‘Ketika Bantuan Internasional Hilang Secepat Sinyal di Hutan Beton: Drama HIV di Afrika Selatan’.
Setengah tahun setelah pengumuman tersebut, negara dengan jumlah penderita HIV terbanyak di dunia ini harus berjuang keras untuk merawat mereka yang paling rentan. Lebih dari 63.000 orang yang sebelumnya dirawat di 12 klinik yang tutup, kini kehilangan akses. Bahkan, hingga 220.000 orang dilaporkan mengalami gangguan dalam rutinitas pengobatan HIV harian mereka.
Pemerintah Afrika Selatan telah berjanji tidak akan membiarkan penarikan bantuan sekitar $427 juta dari Amerika Serikat meruntuhkan program HIV mereka, yang notabene adalah yang terbesar di dunia. Namun, janji adalah janji, kenyataan di lapangan berkata lain. Para pekerja seks dan komunitas transgender, yang merupakan kelompok paling rentan karena pekerjaan mereka ilegal dan sering mendapat stigma, kini menghadapi dunia baru yang penuh kesulitan dalam mendapatkan obat HIV atau obat pencegah (PrEP).
Salah seorang pekerja seks pengidap HIV dan ibu tiga anak bercerita, dirinya sempat tidak minum obat selama hampir empat bulan. Ia ditolak dari rumah sakit umum, meskipun departemen kesehatan pemerintah mengatakan seharusnya hal itu tidak terjadi. Ketakutan akan kematian dan bagaimana menjelaskan kondisinya kepada anak-anaknya menjadi beban pikiran yang tak tertahankan. Perempuan berusia 37 tahun itu akhirnya berhasil mendapatkan pasokan obat sebulan penuh pada bulan Juni dari sebuah klinik keliling, sebuah inisiatif baru pasca-pemotongan dana.
Namun, pasokan satu bulan itu hanyalah solusi sementara, dan ia tidak tahu apa yang akan dilakukan setelahnya. Cerita serupa juga datang dari pekerja seks lain yang terpaksa membeli obat secara ilegal di pasar gelap. Harga pil di pasar gelap ini melonjak hingga dua kali lipat, menambah beban finansial yang sudah berat. Situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem pendukung kesehatan mereka.
Amerika Serikat memang telah mengeluarkan keringanan terbatas yang memungkinkan dimulainya kembali layanan HIV penyelamat jiwa secara global, tetapi kerusakan sudah terjadi. Penarikan sebagian besar bantuan asing AS telah menciptakan kekacauan yang meluas. Bagi banyak orang yang terkena dampak, luka sudah terukir dan proses pemulihan tidak semudah membalik telapak tangan.
Para ahli memperingatkan bahwa tanpa pemulihan bantuan atau penggantian dana dari sumber lain, Afrika Selatan bisa melihat ratusan ribu infeksi baru dalam beberapa tahun ke depan. Diperkirakan juga akan ada puluhan ribu kematian tambahan, sebuah skenario plot twist yang tidak pernah diinginkan. Ini adalah pertaruhan besar yang mengancam kembali kemajuan yang telah dicapai dengan susah payah selama bertahun-tahun.
Ketika Bantuan Medis Pensiun Dini: Drama di Johannesburg
Salah satu tantangan utama bagi mereka yang kehilangan akses ke klinik nirlaba yang didanai AS adalah mencari bantuan di tempat lain, termasuk rumah sakit umum. Pekerja seks berusia 37 tahun itu mencoba tiga klinik lokal, tetapi semuanya menolak memberinya perawatan karena ia tidak memiliki surat rujukan dari klinik sebelumnya. Meskipun Kate Rees, seorang spesialis kesehatan masyarakat di Anova Health Institute di Johannesburg, menegaskan bahwa surat rujukan tidak wajib dan pasien tidak boleh ditolak, realitas di lapangan berbeda. Para staf di klinik, mulai dari perawat, penjaga keamanan, hingga dokter, kerap kali menolak mereka.
Menanggapi pertanyaan Associated Press, Foster Mohale, juru bicara departemen kesehatan Afrika Selatan, menyatakan ketidaktahuan atas insiden penolakan tersebut. Ia mendorong masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan umum terdekat jika mengalami kesulitan. Namun, pernyataan ini terasa kontras dengan pengalaman pahit banyak pasien di lapangan. Kesenjangan antara kebijakan di atas kertas dan praktik di lapangan menjadi masalah serius yang harus segera diatasi.
Misi Mencari Obat: Antara Surat Sakti dan Respon Layanan yang Kurang Friendly
Tantangan lain di rumah sakit dan klinik umum adalah diskriminasi, terutama bagi pekerja seks dan komunitas transgender. Seorang wanita transgender bercerita bahwa di rumah sakit, ia hanya diberi tahu PrEP diberikan kepada pasangan yang salah satunya positif HIV dan sedang berupaya punya bayi. Merasa dipermalukan, ia memutuskan untuk membeli obat secara pribadi dan bahkan pindah ke rumah ibunya demi menghemat uang. Ia bertekad tidak akan kembali ke klinik yang membuatnya merasa seperti badut. Departemen kesehatan tidak menanggapi pertanyaan mengenai isu sensitif ini, menambah keraguan akan komitmen mereka dalam melindungi semua lapisan masyarakat.
Tidak semua orang mampu membeli obat secara pribadi atau melalui pasar gelap, di mana sebotol pil bisa dihargai sekitar $25. Selain harganya yang mencekik, isi dari pil-pil tersebut juga tidak terverifikasi, menimbulkan risiko kesehatan yang lebih besar. Ini adalah pilihan dilematis: antara tanpa obat sama sekali, atau obat dengan potensi bahaya.
Penarikan diri dari layanan kesehatan reguler oleh pekerja seks dan kelompok rentan lainnya memiliki efek domino yang mengerikan. Banyak dari mereka tidak lagi menjalani tes rutin, sehingga tidak tahu tingkat virus HIV dalam tubuh mereka. Ini berarti mereka tidak bisa mengontrol penyebaran virus, menjadi bom waktu kesehatan masyarakat yang sewaktu-waktu bisa meledak. Kurangnya data juga mempersulit upaya penanggulangan secara efektif.
Saat Angka Infeksi Naik Drastis: Plot Twist yang Tidak Kita Inginkan
Bahkan sebelum pemotongan bantuan AS, sekitar 2 juta dari perkiraan 8 juta orang di Afrika Selatan yang hidup dengan HIV tidak pernah mengonsumsi obat secara teratur. Alasan bervariasi, mulai dari tidak punya waktu atau uang untuk biaya perjalanan ke klinik, hingga denial atau ketidakpercayaan terhadap obat-obatan. Banyak juga yang belum terdiagnosis sama sekali. Kini, dengan pemotongan dana ini, angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat, menambah daftar panjang tantangan kesehatan di negara tersebut.
Yvette Raphael, salah satu pendiri kelompok Advokasi Pencegahan HIV dan AIDS setempat, mengungkapkan kekhawatirannya. Ia dan sesama aktivis takut bahwa Afrika Selatan bisa mengalami kemunduran signifikan dalam perang melawan HIV. “Kami takut akan melihat orang-orang meninggal lagi,” ujarnya, sebuah pernyataan yang menyoroti betapa gentingnya situasi ini. Ini bukan hanya masalah statistik, melainkan tragedi kemanusiaan yang nyata.
Utang Triliunan vs. Nyawa Jutaan: Perdebatan ala Hollywood
Kekhawatiran ini bergema di seluruh Afrika, benua yang paling terpukul oleh pemotongan bantuan AS. Pemerintahan Trump membela keputusannya dengan argumen bahwa pengeluaran tersebut tidak selaras dengan kepentingan Amerika Serikat. Russell Vought, Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran AS, dalam sebuah dengar pendapat bulan Juni, menyatakan, “Dan kita memiliki utang $37 triliun. Jadi pada suatu titik, benua Afrika perlu menanggung lebih banyak beban dalam menyediakan layanan kesehatan ini.”
Di kalangan warga Afrika Selatan, ada yang bertanya-tanya apakah sikap Trump mungkin dipengaruhi oleh Elon Musk, warga negara mereka, yang mengawasi upaya awal pemotongan bantuan AS. Terlepas dari motifnya, dampak dari keputusan ini sangat personal dan menyakitkan. Seorang wanita transgender mengungkapkan perasaannya dengan lugas, “Saya tidak punya kata-kata sopan untuk mengungkapkan perasaan saya, tetapi saya hanya membenci mereka atas apa yang mereka lakukan. Hidup kami penting.” Sebuah pengingat pedih bahwa di balik setiap kebijakan besar, ada kehidupan manusia yang dipertaruhkan.
Pemotongan bantuan internasional untuk program HIV di Afrika Selatan, meskipun dikemas dalam retorika kepentingan nasional dan efisiensi anggaran, telah memicu krisis kemanusiaan yang nyata. Dampaknya terasa langsung pada individu-individu yang paling rentan, memaksa mereka berjuang sendiri di tengah sistem yang masih memiliki banyak celah. Ini bukan hanya tentang angka-angka atau kebijakan politik, melainkan tentang kehidupan, harapan, dan martabat manusia yang terancam. Sebuah tamparan keras bagi upaya global dalam memerangi HIV/AIDS, dan pengingat bahwa keputusan di meja-meja kekuasaan seringkali memiliki konsekuensi yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan.