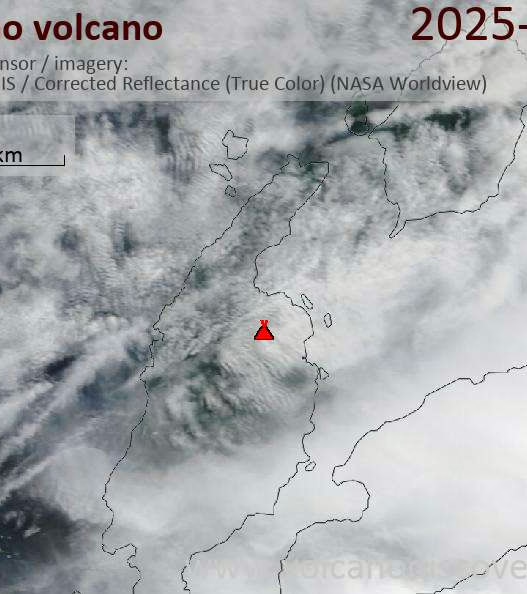Tragedi di Lautan Lepas: Ketika Ikan yang Kita Makan Memakan Korban
Bayangkan jari-jari remuk, rasa sakit tak tertahankan selama sebulan penuh, dan terpaksa mengoperasi diri sendiri dengan nail clipper dan tusuk gigi. Ini bukan adegan dari film horor indie, tapi realita pahit yang dialami Silwanus Tangkotta, seorang nelayan migran Indonesia yang bekerja di kapal ikan Taiwan. Kisahnya hanyalah puncak gunung es dari eksploitasi yang merajalela di industri perikanan jarak jauh Taiwan.
Taiwan memang dikenal sebagai mercusuar demokrasi dan HAM di Asia. Mereka bangga dengan legalisasi pernikahan sesama jenis dan reputasi sebagai negara progresif. Tapi, di balik gemerlap itu, tersembunyi sisi gelap perlakuan terhadap pekerja migran, terutama di sektor perikanan. Ironis, bukan? Seolah-olah kebebasan berekspresi hanya berlaku di daratan, tidak di lautan.
Industri perikanan jarak jauh Taiwan adalah yang terbesar kedua di dunia. Tuna, cumi-cumi, dan hasil laut lainnya dari perairan terpencil ini memenuhi rak supermarket di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Tapi, di balik setiap gigitan sushi lezat, ada kemungkinan jejak keringat dan air mata para pekerja migran yang dieksploitasi.
Sejak 2020, Departemen Tenaga Kerja AS telah memasukkan industri perikanan Taiwan ke dalam daftar yang menunjukkan indikasi kerja paksa. Laporan tersebut menyoroti masalah rekrutmen yang menipu, penahanan upah, kekerasan fisik, dan jam kerja ekstrem. Kita semua suka diskonan, tapi harga murah ikan jangan sampai dibayar dengan penderitaan orang lain.
Pemerintah Taiwan membantah tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai informasi “tidak terverifikasi” dari LSM. Mereka mengklaim telah menerapkan rencana aksi konkret untuk melindungi hak-hak nelayan migran. Tapi, kenyataannya, para pekerja seperti Tangkotta masih menghadapi pelecehan berat, seringkali tanpa perhatian publik yang memadai.
Kisah Tangkotta hanyalah satu dari ribuan cerita serupa. Tergiur dengan janji gaji yang lebih baik ($550 USD, lumayan kalau dibandingkan dengan upah di Indonesia yang kurang dari $100 USD per bulan), mereka meninggalkan keluarga demi mencari nafkah di lautan yang ganas. Namun, realita yang mereka hadapi jauh dari impian.
Bekerja hingga 18 jam sehari, makanan yang tidak mencukupi, isolasi ekstrem tanpa akses internet untuk menghubungi keluarga atau mencari bantuan adalah makanan sehari-hari mereka. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya perlindungan hukum, karena nelayan migran tidak termasuk dalam Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Taiwan. Jadi, kalau terjadi apa-apa, ya nasib-nasiban.
Eksploitasi di Tengah Laut: Jeritan Nelayan Migran
Eksploitasi pekerja migran di laut lepas menjadi isu serius yang memerlukan perhatian mendalam. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum membuat para pekerja rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM.
Insiden yang dialami Tangkotta, dimana ia harus mengobati luka sendiri selama sebulan penuh karena kapten kapal menolak kembali ke pelabuhan, adalah contoh nyata. Ini bukan lagi masalah kurang perhatian, tapi sudah masuk kategori kejahatan kemanusiaan. Bayangkan kalau itu terjadi pada kita?
Yilan Migrant Fishermen Union, sebuah LSM yang berbasis di Taiwan, menyebutkan bahwa meskipun AS telah melabeli industri perikanan Taiwan sejak 2020, pemerintah hanya merespons dengan retorika tanpa perubahan signifikan. Janji gaji layak hanyalah omong kosong belaka, karena banyak pekerja mengalami kerja paksa dan upah yang ditunda.
WiFi untuk Nelayan: Solusi Sederhana, Dampak Luar Biasa
Salah satu solusi yang diusulkan adalah menyediakan akses WiFi untuk semua nelayan migran. Ini bukan soal biar mereka bisa update status di Instagram, tapi agar mereka bisa memeriksa gaji, menghubungi keluarga, dan mencari bantuan dari LSM, bahkan dari tengah lautan. Ini sama pentingnya dengan pelampung keselamatan.
Selain itu, peraturan yang melarang pekerja migran berganti pekerjaan tanpa kembali ke negara asal atau membayar biaya agensi baru juga harus dihapuskan. Peraturan ini membuat pekerja takut melaporkan pelecehan, karena takut dipecat dan terlilit hutang. Bukannya melindungi, malah menjerat.
Achmad Mudzakir, pemimpin FOSPI, sebuah LSM yang berbasis di Taiwan, mengatakan bahwa pencurian upah adalah salah satu masalah paling luas yang dihadapi oleh nelayan migran. Dampaknya sangat menghancurkan bagi keluarga mereka di kampung halaman.
Tuna di Meja Makan, Darah di Lautan
Konsumen di seluruh dunia, termasuk kita, perlu menyadari bahwa makanan laut yang kita konsumsi mungkin saja berasal dari hasil eksploitasi. Taiwan adalah eksportir makanan laut terbesar ketujuh di dunia. Jadi, setiap kali kita makan sushi, pikirkan lagi dari mana ikan itu berasal. Apakah ada cerita pilu di baliknya?
“Konsumen Amerika masih berisiko tinggi mengonsumsi makanan laut yang tercemar perbudakan modern,” kata Sari Heidenreich, penasihat senior hak asasi manusia Greenpeace AS. Perusahaan yang mengimpor makanan laut dari Taiwan harus memeriksa rantai pasokan mereka dengan lebih ketat. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal etika dan kemanusiaan.
Bahkan, empat nelayan Indonesia mengajukan gugatan federal terhadap raksasa makanan kaleng AS, Bumble Bee Foods, yang dimiliki oleh konglomerat makanan laut Taiwan, FCF Co. Mereka menuduh Bumble Bee “dengan sengaja mendapat keuntungan” dari kerja paksa dan pelanggaran lainnya dalam rantai pasokan mereka. Ini adalah kasus pertama perbudakan di kapal ikan yang dibawa ke pengadilan terhadap perusahaan makanan laut AS.
Harapan di Tengah Keputusasaan
Silwanus Tangkotta, yang kini bergantung pada bantuan teman dan keluarga, berharap tidak ada lagi orang lain yang mengalami nasib serupa. “Saya berharap semua teman saya – semua saudara saya – yang bekerja di kapal Taiwan menerima perawatan yang layak jika mereka terluka di laut,” katanya.
“Saya berharap ini hanya terjadi pada saya, dan tidak lagi pada nelayan lain.” Ini bukan hanya sekedar harapan, tapi juga seruan untuk bertindak. Kita semua punya peran untuk memastikan bahwa tragedi seperti ini tidak terulang lagi.
Kisah Silwanus adalah pengingat keras bahwa di balik setiap produk yang kita nikmati, ada cerita manusia yang mungkin terlupakan. Jangan biarkan rasa nyaman dan convenience membuat kita menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Sudah saatnya kita lebih peduli dan menuntut perubahan. Ingat, ikan yang kita makan seharusnya memberi kita energi, bukan rasa bersalah.