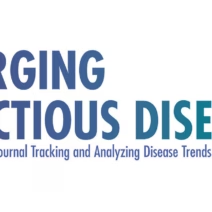Dunia musik itu kayak ujian skripsi: penuh kejutan, kadang bikin pengen nangis, tapi ujung-ujungnya harus dihadapi. Nah, Twenty One Pilots (TOP) ini ibarat mahasiswa abadi yang nggak pernah lulus dari eksperimen musik. Dengan album terbaru mereka, “Breach”, apakah mereka akhirnya nemu formula yang pas, atau malah terjebak di siklus yang itu-itu aja? Mari kita bedah, sambil ngopi tentunya.
“City Walls”: Antara Fan Service dan Kebingungan Identitas
Pembuka album, “City Walls,” adalah rangkuman lengkap dari TOP. Ada hook yang catchy, chorus yang menggelegar, bass yang fuzzy, drum yang overdriven, dan tentu saja, rap ala Tyler Joseph. Video musiknya yang konon menghabiskan sejuta dolar itu adalah parade referensi ke karya-karya lama mereka. Ini seperti reuni akbar alumni yang meriah, tapi sedikit overwhelming buat pendatang baru. Yang menarik, band yang kerap diasosiasikan dengan nilai-nilai Kristen ini mengulang lirik “entertain my faith” dalam video yang menggambarkan Clancy, karakter fiksi mereka, menyerah pada sekte agama. Ironis, tapi sayangnya nggak digali lebih dalam.
Setelah menyumbang lagu untuk Suicide Squad, TOP kini memancarkan energi yang mirip dengan film Superman-nya James Gunn. “The Contract” dengan breakbeat ala game snowboarding dan vokal yang diproses gila-gilaan tetap asyik dinikmati, meski tanpa tahu menahu soal kekuatan sihir para Bishop (karakter fiksi di dunia TOP). Ada juga kejenakaan khas TOP di lagu “Garbage,” yang mengejek piano part ala “Something Just Like This” sebelum Tyler Joseph tiba-tiba berteriak, “I feel like garbage!” Di “Rawfear,” tempo lagu tiba-tiba dipercepat saat lirik “never slowing down” dinyanyikan, lalu kembali ke tempo semula. Ini seperti kode bahwa karakter di lagu itu nggak bisa kabur dari siklusnya.
Mendekati akhir album, ada “Cottonwood,” tribut untuk kakek Tyler Joseph, dan “Intentions” yang meditatif. Ada juga “Downstairs,” demo lama mereka yang dipoles ulang. Tapi, keseriusan yang tersisa dari lagu itu terasa nggak pas di album yang lebih ceria ini. Ini kayak pakai jas hujan di pantai – fungsional, tapi salah kostum.
Dilema Hip-Hop ala Twenty One Pilots: Cuma Tempelan?
Salah satu hal yang bikin gregetan dari TOP adalah kecenderungan mereka untuk memasukkan unsur hip-hop ke dalam musik mereka. Tyler Joseph pernah memberikan daftar musisi yang memengaruhinya ke Zane Lowe, dan dari sekian banyak nama, cuma ada satu rapper: Matisyahu. Di “Breach,” mereka terdengar seperti sekilas mendengarkan album GNX-nya Kendrick Lamar. Tapi, keterlibatan mereka dengan genre ini masih dangkal. Nggak ada yang lebih nggak meyakinkan daripada Tyler Joseph yang menyanyikan lirik “empty Uzis” di lagu “Rawfear.” Ini seperti anak kuliahan sok jadi gangster – niatnya keren, tapi hasilnya malah cringe.
Twenty One Pilots ini kayak mie instan. Kadang bumbunya pas, bikin nagih. Tapi, kadang bumbunya kebanyakan, jadi eneg. “City Walls” adalah contoh yang pertama: terlalu banyak elemen yang dijejalkan jadi satu. Sementara “The Contract” lebih minimalis dan fokus, hasilnya lebih enak dinikmati.
Relasi Kompleks Tyler Joseph dan Fans: Pedang Bermata Dua
Salah satu tema yang paling menarik dari musik TOP adalah hubungan kompleks Tyler Joseph dengan para penggemarnya. Di lagu “Guns for Hands” dari album Vessel, dia merasa bertanggung jawab atas kesehatan mental para penggemarnya, sementara kesehatan mentalnya sendiri justru memburuk. Di balada “Neon Gravestones” dari album Trench, dia memperingatkan penggemarnya untuk nggak mengagungkan kematiannya kalau suatu hari dia kalah dalam melawan depresi. Ketegangan ini mencapai puncaknya di album Breach.
Awal tahun ini, seorang penggemar sempat mencuri bass drum dari drum kit-nya Josh Dun saat konser. Di lagu “Center Mass,” band ini menyertakan sampel suara seorang penggemar yang memperingatkan, “I really don’t think you should take that!” Di lagu “Drum Show,” Tyler Joseph memberikan penghormatan kepada Josh Dun yang kelelahan, yang “terjebak di antara batu dan rumah, dua tempat yang nggak ingin dia datangi.” Ketika Tyler Joseph mengatakan, “This has not been interesting in a while” di lagu “One Way,” band ini secara jujur mengakui adanya disilusi. Ini seperti pasangan yang sudah lama menikah dan mulai bosan dengan rutinitas, tapi tetap berusaha untuk mempertahankan hubungan.
Kapan Twenty One Pilots Dapat “Pengakuan”?
Saat ini, sulit membayangkan Twenty One Pilots akan mendapatkan re-evaluasi budaya seperti yang dialami My Chemical Romance dan Linkin Park. Tapi, melihat band seperti MGK mencoba gaya serupa tanpa ambisi yang sama, kita jadi bisa lebih menghargai apa yang sudah dilakukan TOP. Mereka mungkin akan lebih dihormati kalau menghilangkan rap sama sekali, tapi itu akan mengubah esensi dari band ini. Sama seperti nasi goreng tanpa kecap – tetap nasi goreng, tapi rasanya jadi kurang nendang.
“Breach”: Akhir yang Menggantung
Nasib Clancy, karakter fiksi yang menjadi benang merah di album-album TOP, masih belum jelas. Dia gagal memutus siklus dan, dalam twist ala Matrix Reloaded, para pemberontak harus mencari “Clancy” lain untuk melanjutkan perjuangan. Ini adalah akhir yang pahit: nggak ada yang benar-benar bisa melampaui keterbatasan mereka. Tapi, ini juga jadi harapan bahwa mereka akan terus mencoba lagi. Sama seperti kita yang terus berusaha untuk menjadi lebih baik, meski seringkali gagal. Setidaknya, kita nggak menyerah, kan?
Pada akhirnya, “Breach” adalah album yang jujur dan kompleks. Twenty One Pilots nggak takut untuk bereksperimen dan mengeksplorasi tema-tema yang berat. Meski nggak semua eksperimen berhasil, tapi keberanian mereka patut diacungi jempol. Album ini mungkin nggak akan mengubah dunia, tapi setidaknya bisa jadi teman yang menemani kita di tengah kebimbangan dan kegelisahan hidup.