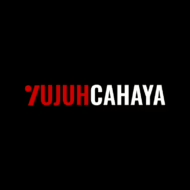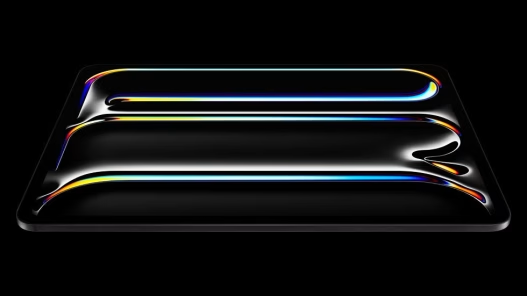Apakah alam adalah milik kita semua atau beberapa "kita" saja? Pertanyaan filosofis ini ternyata jadi isu nyata dalam pembahasan Undang-Undang (UU) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang baru direvisi. Banyak yang khawatir, revisi ini justru bisa menjadi pedang bermata dua, melindungi alam di satu sisi, tetapi mengancam hak-hak masyarakat adat di sisi lainnya. Ibaratnya, mau masak nasi goreng tapi malah membakar dapur.
Konservasi Alam vs. Hak Masyarakat Adat: Sebuah Dilema Abadi?
Polemik seputar UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang baru ini bukan sekadar debat kusir. Ini adalah pertarungan antara idealisme konservasi dengan realitas sosial dan kultural yang sudah berurat akar di Indonesia. UU No. 32/2024 ini, yang merupakan revisi dari UU konservasi tahun 1990, bertujuan untuk memperkuat upaya pelestarian alam. Tujuannya mulia, memang.
Namun, ada beberapa pasal yang membuat bulu kuduk merinding para aktivis lingkungan dan organisasi masyarakat sipil. Salah satunya adalah pasal yang memberi kewenangan lebih besar kepada negara dalam menetapkan kawasan konservasi. Masalahnya, banyak wilayah adat yang ternyata masuk ke dalam zona konservasi tersebut.
Hak Waris Dilindas Bulldozer Konservasi?
Menurut Forest Watch Indonesia (FWI), ekspansi wewenang negara dalam menetapkan kawasan konservasi berpotensi menggerus hak-hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka. UU tersebut bahkan menyebutkan bahwa jika ada pemegang hak di kawasan pelestarian yang menolak melakukan kegiatan konservasi, mereka harus melepaskan hak atas tanahnya dengan kompensasi atau menghadapi sanksi pidana. Serius, ini seperti memaksa orang untuk memilih antara rumah dan kebebasan.
Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar: apakah konservasi harus dilakukan dengan mengorbankan hak-hak masyarakat adat? Apakah pelestarian alam hanya bisa efektif jika masyarakat adat disingkirkan dari wilayahnya sendiri?
Mengapa Suara Masyarakat Adat Terdengar Sumir?
Salah satu kritik utama terhadap UU ini adalah kurangnya partisipasi bermakna dari masyarakat adat selama proses legislasi. Laporan menyebutkan bahwa sekitar 35% wilayah adat kini berada di dalam zona konservasi yang ditetapkan. Namun, suara dan perspektif masyarakat adat justru kurang terdengar dalam perumusan kebijakan.
Ini seperti membuat pesta tanpa mengundang yang punya rumah. Lasti Fardila Noor dari Indigenous and Local Communities Conserved Areas (ICCAs) Indonesia menyoroti masalah ini. Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi kebijakan konservasi.
Ketika Hukum Jadi Senjata Makan Tuan: Kriminalisasi di Balik Konservasi
Anggi Prayoga dari FWI khawatir bahwa UU ini justru membuka celah untuk meningkatnya kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Alih-alih memperkuat konservasi, hukum ini justru berpotensi menjadi alat untuk menyingkirkan masyarakat adat dari tanah leluhur mereka dengan dalih pelestarian lingkungan.
Ini ironis, bukan? UU yang seharusnya melindungi alam, malah bisa digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang selama berabad-abad menjaga dan melestarikan alam secara tradisional.
Mahkamah Konstitusi: Harapan Terakhir?
Di tengah kekhawatiran dan ketidakpastian ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi harapan terakhir bagi banyak pihak. Organisasi masyarakat sipil telah mendesak MK untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dalam meninjau kembali UU Konservasi SDA dan Ekosistem yang baru direvisi ini.
Semoga saja MK bisa menjadi penengah yang adil antara kepentingan konservasi dan hak-hak masyarakat adat. Keputusan MK akan sangat menentukan nasib masyarakat adat dan masa depan konservasi alam di Indonesia.
Melawan Lupa: Mengapa Ingatan Kolektif Itu Penting
Sejarah kelam perampasan tanah masyarakat adat atas nama pembangunan dan konservasi harus menjadi pelajaran berharga. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Ingatan kolektif tentang bagaimana kebijakan yang buruk bisa merugikan banyak orang harus terus dipelihara.
Menuju Konservasi yang Berkeadilan: Solusi Jangka Panjang
Lalu, bagaimana solusinya? Jawabannya sederhana, tapi kompleks: konservasi yang berkeadilan. Ini berarti konservasi yang tidak hanya fokus pada pelestarian alam, tetapi juga memperhatikan dan melindungi hak-hak masyarakat adat.
Konservasi yang berkeadilan membutuhkan:
- Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.
- Partisipasi bermakna masyarakat adat dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi kebijakan konservasi.
- Penyelesaian konflik agraria secara adil dan transparan.
- Pengembangan model konservasi yang berbasis pada kearifan lokal masyarakat adat.
Konservasi yang berkeadilan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa pelestarian alam tidak dilakukan dengan mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Konservasi yang hakiki adalah yang merangkul, bukan yang mengucilkan.
Investasi Masa Depan: Konservasi yang Berkelanjutan
Konservasi yang berkeadilan adalah investasi masa depan. Dengan melindungi hak-hak masyarakat adat dan melibatkan mereka dalam upaya pelestarian alam, kita tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Ini win-win solution, guys!
Memastikan Warisan Alam Tetap Lestari
Jangan sampai generasi mendatang hanya bisa melihat hutan dan sungai di buku pelajaran saja. Kita harus memastikan bahwa warisan alam yang berharga ini tetap lestari, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak cucu kita.
Pelestarian alam dan perlindungan hak-hak masyarakat adat bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya bisa dan harus berjalan beriringan. Dengan gotong royong dan niat baik, kita bisa menciptakan konservasi yang tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat adat. Masa depan bumi ada di tangan kita, jadi mari kita jaga bersama.